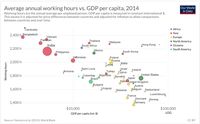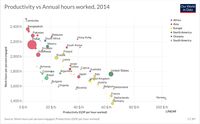Seringkali, periode krisis dapat menyebabkan perhatian
hanya berfokus pada jangka pendek dan dalam aspek negatif yang dapat mengarah
pada kesimpulan yang tidak akurat. Tentu saja Indonesia menghadapi periode yang
rumit dalam perdagangan internasionalnya. Ekspor Indonesia mulai secara
bertahap kembali menguat setelah jatuh pada tahun 2014. Masalah nyatanya adalah
bahwa tekanan impor yang tumbuh lebih cepat daripada ekspor. Secara garis
besar, ekspor barang meningkat dari US$66 miliar pada tahun 2004 menjadi lebih
dari US$168 miliar pada 2017. Namun, impor barang meningkat dari US$46 miliar
menjadi US$150 milar. Di bidang jasa, Indonesia secara historis menghadapi defisit
perdagangan. Total neraca perdagangan Indonesia sejak 2012 berubah dari surplus
menjadi defisit. Namun, ada baiknya kita bertanya, apa yang telah terjadi dalam
dekade terakhir perdagangan internasional di Indonesia?
Secara umum, sulit untuk menyimpulkan apa yang
telah terjadi pada perdagangan Indonesia dan apakah dalam beberapa tahun
terakhir pembukaan perdagangan telah menguntungkan atau merugikan
Indonesia. Puncak ekspor Indonesia terjadi pada tahun 2011 dengan nilai
US$203 miliar. Setelah tahun 2011 ekspor turun, antara lain karena harga
komoditas dan permintaan di pasar tradisional yang drop secara besar. Nilai
ekspor mineral drop -52% antara tahun 2010 dan 2017, bahan bakar turun -21%,
dan plastik -12%. Pada tahun 2012, saat bonanza dari harga tinggi dalam
komoditas memudar, nilai ekspor komoditas runtuh, sedangkan Indonesia tidak
siap menghadapi turunnya pasar. Namun, Indonesia mendapatkan udara segar
dengan munculnya permintaan untuk produk tanaman (vegetable oils),
produk kimia, batu (stone) dan kaca. Demikian juga, Indonesia berhasil keluar
dari defisit dalam produk kendaraan transportasi dan menjadi surplus. Ada pula
produk kayu, alas kaki, tekstil, dan produk hewani juga mendukung pertumbuhan
positif dalam ekspor.
Tapi apa yang terjadi pada level produk
berdasarkan proses atau penggunaannya? Sejak lama, Indonesia memiliki neraca
perdagangan defisit di barang modal pada hampir semua kategori di bawah Capital
Goods. Defisit masih di atas US$27 miliar dan belum ada sinyal positif bahwa
Indonesia dapat membalik defisit perdagangan barang modal. Kelompok produk lain
yang juga menghadapi beberapa kesulitan adalah produk setengah jadi. Setelah tahun 2012, produk/barang setengah jadi
(Intermediate Goods) mengalami defisit dan mencapai sekitar US$5,4 miliar pada
tahun 2017. Bahan kimia, barang logam, dan aluminium (termasuk besi - baja),
pupuk, plastik, dan barang setengah jadi untuk sektor tekstil juga memberikan
tekanan pada neraca perdagangan. Ada beberapa sektor manufaktur utama di
Indonesia juga yang sangat bergantung pada barang setengah jadi dari luar
negeri.
Sampai sekarang jenis produk yang paling
mendukung surplus perdagangan di Indonesia adalah Consumer Goods dan Raw
Materias. Surplus Terbesar di Indonesia terjadi pada Consumer Goods yaitu US$26
miliar termasuk antara lain alas kaki, pearls (perhiasan), pakaian, dan
furniture. Raw Materials juga memberikan surplus besar yaitu US$16 miliar
terutama antara lain dari batubara, tembaga, nikel, palm Oil. Namun,
ekspor bahan mentah turun lebih dari 50% dari tahun 2010 hingga 2017, karena
harga komoditas yang jatuh. Dalam barang-barang setengah jadi, Indonesia telah
mengembangkan beberapa sektor terbaik antara lain pada bijih, kayu, karet,
kertas, barang kimia, mutiara, timah, dan serat stapel. Kebijakan untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam sektor nikel, tembaga, aluminium, baja dan
barang lainnya juga mendukung ekspor barang dengan nilai tambah lebih besar di
bawah barang setengah jadi yang memberi surplus sekitar US$17 miliar.

Faktor lain yang memberikan perspektif lebih
tepat tentang apa yang terjadi dengan perdagangan di Indonesia adalah hubungan
dengan mitra dagang utama. Sejak dua dekade terakhir, Indonesia telah
menandatangani beberapa perjanjian perdagangan internasional. Saat ini,
Indonesia memiliki perjanjian perdagangan dengan lebih dari 17 negara yang
telah berlaku dan lebih dari 20 perjanjian yang sedang dipelajari atau akan
segera diratifikasi. Di antara perjanjian yang ditandatangani, Indonesia
meningkatkan neraca perdagangan barang dengan India (surplus lebih dari US$10
miliar), Amerika Serikat (US$10 miliar), Filipina (US$5,7 miliar, Pakistan
(US$2 miliar), Hong Kong, Chile, Belanda, Swiss, Kamboja, Brunei, dan Myanmar.
Sedangkan dengan negara-negara lain neraca perdagangan Indonesia juga telah
membaik, namun keseimbangan tetap negatif pada negara Selandia Baru, Singapura,
dan Thailand.Namun dengan negara mitra lainnya, Indonesia memperburuk posisi
komersialnya seperti dengan China yang defisit US$ 11 miliar, Australia -US$4,5
miliar, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Laos, Vietnam, Iran, Jerman, dan
Turki. Dengan Australia, ekspor turun 41%, sementara impor meningkat 72%.
Dengan China, ekspor tumbuh 47%, namun impor naik lebih cepat (hampir
70%).
Indonesia memperoleh surplus besar dengan Cina
di dalam produk hewani dan nabati, pada bahan bakar, kayu, dan alas kaki,
tetapi mengalami kerugian besar pada mesin, bahan kimia, tekstil, dan logam.
Dengan Korea dan Jepang ekspor turun lebih dari 30% sejak 2007 menyebabkan
penurunan yang signifikan dalam neraca perdagangan. Secara umum,
perdagangan yang mungkin paling menguntungkan Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir sejak 2007 adalah dengan Amerika Serikat, India, Pakistan,
negara-negara ASEAN, sebagian Eropa, dan dengan negara mitra baru yaitu Afrika,
Timor Tengah, dan Amerika Latin sebagian besar meningkatkan neraca perdagangan.
Indonesia telah mengubah orientasi ekspornya untuk menjadi eksportir produk dan
bahan mentah, serta reorientasi ke pasar di negara-negara di Asia (Timur,
Selatan, dan tenggara).
Indonesia telah menjadi pemain regional yang
lebih kuat, namun kehilangan sebagian dari pasar globalnya terhadap eksportir
lain (Cina). Sangat memungkinkan bahwa orientasi yang berlebihan terhadap bahan
baku menyebabkan Indonesia mengesampingkan peluang dalam produk manufaktur di
mana pertumbuhan dipercepat dan lebih stabil. Orientasi yang berlebihan untuk
memenuhi permintaan pasar bahan mentah dan produk menyebabkan Indonesia
mengesampingkan peluang dalam produk manufaktur di mana pertumbuhan dipercepat
dan lebih stabil. Di sektor teknologi komunikasi, transportasi, elektronik, dan
permesinan, pembangunan Indonesia secara proporsional lebih rendah daripada
negara-negara tetangga yaitu Asia.
Pada dekade terakhir perdagangan
internasional, Indonesia terlihat lebih dinamis dan lebih positif. Sementara
sekitar 65% dari ekspor Indonesia yaitu 471 produk, telah menjadi tulang
punggung ekspor sejak tahun 2005. Ada daftar panjang dari produk baru yang
telah memperoleh daya saing dan kini berkontribusi dengan lebih dari 20% dari
ekspor Indonesia yaitu sekitar 250 produk. Persaingan besar juga telah
menghasilkan kerugian sekitar 400 produk kehilangan daya saing. Namun, nilai
ekspor produk baru telah menghasilkan lebih dari nilai kerugian. Indonesia
tidak bisa membiarkan tekanan dari neraca perdagangan yang negatif dan harus
mampu mencegah serta melihat peluang. Jika Anda melihat ukuran peluang
komersial dari produk yang sekarang memiliki keunggulan komparatif di
Indonesia, hanya Jepang, Cina, Australia, Selandia Baru, India dan Hong Kong
yang mengimpor lebih dari US$400 miliar produk-produk di mana Indonesia yang
kompetitif. Berarti Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan pasar
itu dengan produk yang sekarang sudah unggul. Sedangkan negara-negara ASEAN,
mengimpor US$30 miliar lagi dari produk-produk yang sama.

Aspek lain yang patut dipertimbangkan adalah
dampak ekspor terhadap kesejahteraan. Salah satu indikator yang dapat
memberikan beberapa sinyal manfaat adalah distribusi pendapatan di antara
pemain di pasar (produsen). Ada dua aspek dalam ekspor Indonesia yang
menarik untuk dicatat. Yang pertama adalah persentase nilai tambah yang
diterima pekerja dari produk ekspor meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2011 (data terakhir), untuk setiap dolar yang diekspor, US$ 0,33 sen
berhubungan dengan pendapatan pekerja, dengan US$0,275 untuk pekerja tanpa
keterampilan (unskilled workers). Pada tahun 1995, pekerja hanya menerima 21%
dari nilai ekspor. Indikator kedua adalah partisipasi tidak langsung dalam
ekspor, khususnya bagi UKM. Pada tahun 2011 perusahaan UKM berkontribusi dengan
sekitar 18% dari nilai ekspor. Namun, dengan berpartisipasi secara tidak
langsung (memasok bahan untuk eksportir) perusahaan UKM meningkatkan ekspor
mereka ke angka yang lebih dari 23%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam
tujuh tahun terakhir, "kue" ekspor Indonesia hampir tiga kali lebih
besar, memiliki "irisan" yang lebih besar untuk para pekerja dan UKM,
dan termasuk "rasa" baru, yaitu rasa Asia dengan rasa lebih alami
dengan bahan yang tidak banyak diproses.

Reza Faizal Daradjat
Referensi :